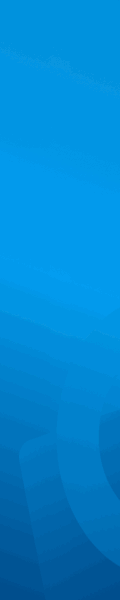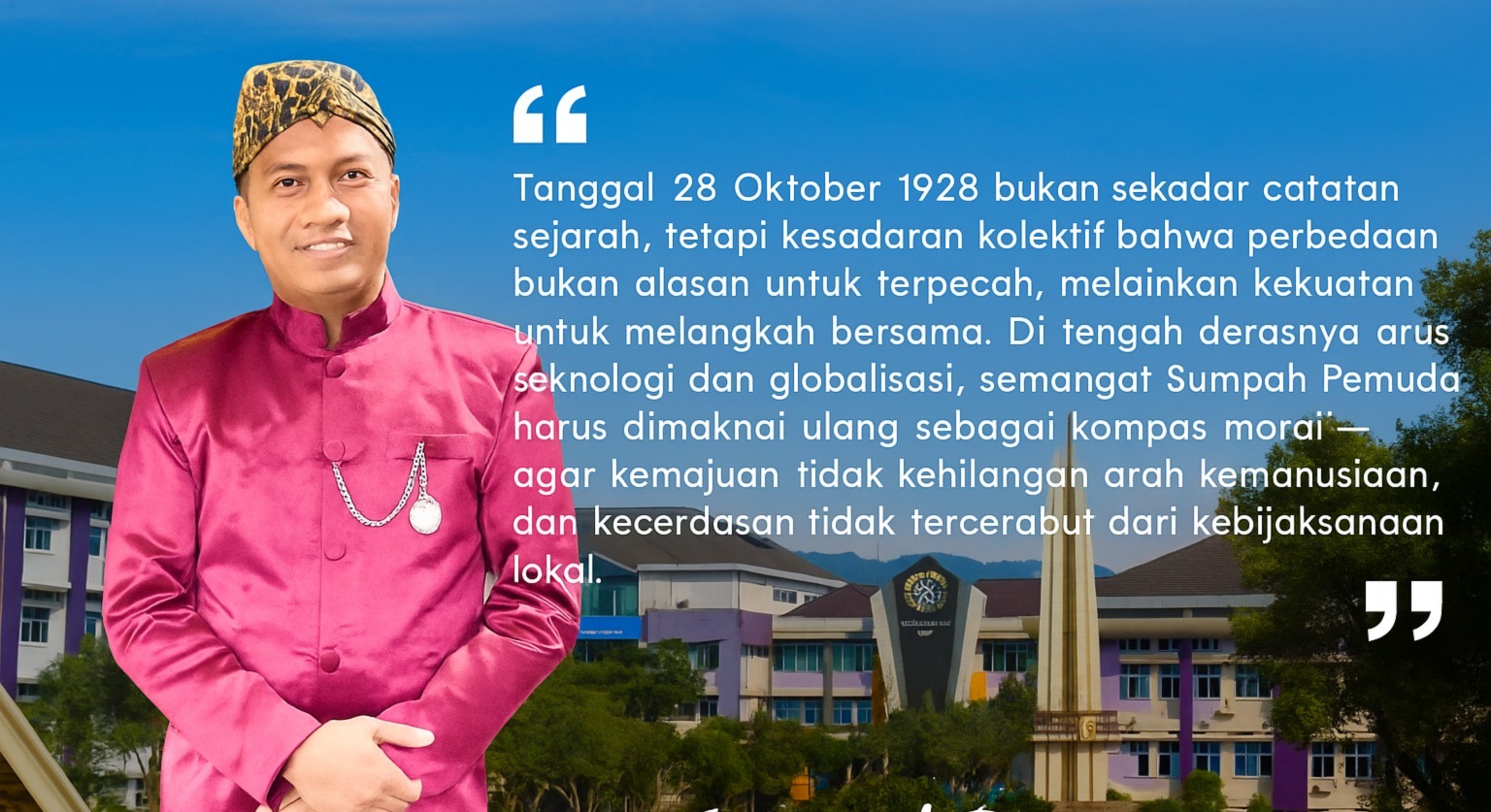Di masa kini, konteksnya memang berbeda, tetapi tantangannya sama: bagaimana membangun bangsa di tengah kompleksitas zaman. Jika dulu tantangan terbesar adalah kolonialisme dan keterbelakangan, maka kini tantangannya adalah globalisasi tanpa arah nilai, di mana kemajuan teknologi kadang tidak diimbangi dengan kedewasaan moral. Pemuda hari ini dituntut untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat dan beretika. Mereka perlu memahami sejarah perjuangan bangsanya, karena bangsa yang kehilangan kesadaran sejarah akan mudah kehilangan jati diri. Sejarah tidak hanya untuk dihafal, tetapi untuk dihayati sebagai sumber nilai dalam merancang masa depan.
Relasi sejarah pergerakan pemuda di masa lalu dengan konteks kekinian adalah keterampilan yang adaptif dan inovasi bernilai. Dunia kerja dan kehidupan global menuntut keterampilan baru: berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan literasi digital. Namun keterampilan teknologis saja tidak cukup untuk membangun peradaban. Pembangunan berkelanjutan memerlukan integritas moral dan growth mindset — cara berpikir yang percaya bahwa kemampuan manusia dapat tumbuh melalui usaha, refleksi, dan pembelajaran berkelanjutan. Generasi muda Indonesia perlu memadukan kompetensi digital dengan etika kehidupan. Kemajuan teknologi tidak boleh menjauhkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaan. Artificial intelligence, big data, atau ekonomi digital harus dipahami bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sumpah Pemuda di era digital berarti berkomitmen untuk menguasai teknologi tanpa kehilangan nurani, dan berinovasi tanpa mengorbankan kemanusiaan.
Religiusitas dan Kearifan Lokal sebagai Kompas Moral
Pembangunan berkelanjutan sejatinya bukan hanya soal ekonomi hijau atau teknologi ramah lingkungan, tetapi tentang cara hidup yang berakar pada nilai spiritual dan budaya. Dalam konteks Indonesia, dua sumber nilai yang paling kuat adalah religi dan kearifan lokal (local wisdom). Religiusitas memberi kesadaran bahwa manusia adalah khalifah fil ard (pemimpin di bumi) di bumi, yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam dan sesama makhluk. Sementara kearifan lokal mengajarkan harmoni, gotong royong, dan kesederhanaan dalam hidup. Di berbagai daerah, falsafah lokal seperti silih asih, silih asah, silih asuh (Sunda), tepa selira (Jawa), atau mapalus (Minahasa) menunjukkan bahwa pembangunan sejati selalu berangkat dari kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.