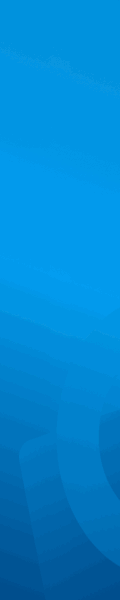REDAKSI.pesanjabar.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pada awal 2025 menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Targetnya ambisius: 82,9 juta penerima, mulai dari anak sekolah dasar hingga menengah, santri pesantren, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Dengan anggaran awal mencapai Rp71 triliun dan kebutuhan hingga 2029 diperkirakan lebih dari US$28 miliar, wajar bila program ini memicu banyak perbincangan: antara harapan besar dan keraguan serius.
Di satu sisi, MBG menjanjikan lompatan penting dalam penurunan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penguatan ekonomi lokal. Di sisi lain, keberlanjutan fiskal, inflasi pangan, kesiapan logistik, hingga potensi fraud menjadi bayangan yang tak bisa diabaikan.
Harapan dan Potensi
Pertama, dari sisi gizi, Indonesia masih menghadapi prevalensi stunting sebesar 21,5% (2023). Intervensi gizi massal dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi mendatang.
Kedua, MBG berpotensi menjadi transformasi sosial besar-besaran, setara dengan kebijakan wajib belajar. Dengan makanan bergizi, anak-anak diyakini lebih konsentrasi, lebih rajin hadir, dan prestasi akademiknya meningkat.
Ketiga, efek ekonomi lokal juga menjanjikan. Model dapur sekolah atau kemitraan dengan UMKM dapat menciptakan pasar stabil bagi petani, nelayan, dan peternak, sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Risiko dan Tantangan
Namun, ada sejumlah tantangan serius. Beban fiskal menjadi yang utama. Dengan biaya yang begitu besar, publik mempertanyakan apakah manfaatnya sepadan dengan pengorbanan pada pos anggaran lain yang tak kalah penting.
Dari sisi teknis, logistik distribusi makanan harian untuk puluhan juta penerima jelas sangat rumit. Risiko makanan basi, keterlambatan distribusi, hingga standar gizi yang tidak seragam bisa saja terjadi.
Ada pula ancaman inflasi pangan akibat lonjakan permintaan telur, ayam, atau susu secara masif. Tanpa mekanisme buffer stock yang efektif, masyarakat umum bisa terkena dampak harga yang melonjak.
Selain itu, skala program yang begitu besar membuka ruang bagi fraud: mulai dari data penerima fiktif, kolusi vendor, hingga mark-up harga per porsi.
Dimensi Sosial dan SDM
Risiko lain juga tak kalah serius. Jika tidak dikelola baik, MBG dapat memicu ketergantungan keluarga pada suplai makanan sekolah, atau menciptakan kesenjangan sosial antara anak di sekolah negeri dan kelompok lain yang tak terjangkau program.
Dari sisi sumber daya manusia, keterbatasan ahli gizi dan tenaga dapur terlatih menjadi masalah krusial. Tanpa standar higienitas dan logistik yang baik, program “makan bergizi” bisa tereduksi menjadi sekadar “makan gratis asal kenyang”.
Belajar dari Dunia dan Sejarah
Sejumlah negara maju telah lama menjalankan program serupa. Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang punya model berbeda, tetapi sama-sama menekankan standar gizi ketat, kombinasi subsidi–kontribusi orangtua, serta pengawasan food safety yang kuat.
Dari perspektif Islam, MBG sejalan dengan maqāṣid syariah: menjaga jiwa dan keturunan. Sejarah Islam pun kaya dengan contoh: Umar bin Khattab mendirikan dapur umum saat paceklik, Umar bin Abdul Aziz memastikan rakyatnya tidak kelaparan, hingga tradisi Imaret di Kesultanan Ottoman yang membagi ribuan porsi makanan gratis setiap hari. Prinsip dasarnya: makanan harus halal, thayyib, adil, dan tidak menimbulkan stigma.
Jalan Tengah yang Rasional
Untuk menjembatani idealisme gizi dengan realitas fiskal, ada beberapa opsi strategis:
Targeting cerdas, memprioritaskan kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan kelas awal SD.
Kontrol anggaran, dengan plafon belanja tahunan dan evaluasi rutin.
Desain anti-inflasi, melalui kontrak multipemasok dan buffer stock Bulog.
Hybrid kitchen model, dapur pusat di perkotaan, UMKM di sekolah/pesantren kecil.
Pengawasan digital, dengan geo-tag, timestamp, hingga audit acak berbasis uji laboratorium.
Diversifikasi pendanaan, bukan hanya dari APBN, tetapi juga CSR pangan dan wakaf produktif.
Penutup
Program MBG adalah kebijakan dengan niat mulia dan potensi transformasi besar. Namun, implementasinya tidak bisa hanya berlandaskan semangat populis. Ia harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang kuat, desain yang realistis, dan keberlanjutan fiskal yang terukur.
Jika MBG berhasil menggabungkan efisiensi dapur pusat, fleksibilitas UMKM lokal, pengawasan digital, serta nilai-nilai keadilan sosial, maka ia berpeluang menjadi legacy kebijakan nasional. Tetapi bila dijalankan tanpa perhitungan matang, program ini bisa berakhir sekadar “proyek besar yang sulit dijaga keberlanjutannya”.
Penulis: Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI)